Saya tidak sedang mengisahkan semua lelaki yang tinggal di Aceh, tapi hanya lelaki dari suku gayo yang tinggal di Takengon, Aceh Tengah.
Seksinya lelaki gayo bisa kita nikmati dalam warung kopi, di atas kerambah ikan dan kebun kopi, serta di terminal. Tempat lelaki biasa beredar.
Saya tiba di Takengon dengan bus pelangi dari Medan pukul 5:30 pagi, 30 Januari. Hotel masih tutup, hari gelap berkabut. Namun merahnya fajar mengantarkan saya untuk menyusuri danau Lut Tawar, laut bagi orang gayo Takengon dan nyawa bagi pemilik kerambah di sana. Saya lihat kehidupan mulai menggeliat. Sungai dipenuhi perempuan yang mencuci dan mandi, jembatan pun berdendang duk duk duk ditingkapi angkot dan becak yang lalu-lalang. Tak berapa lama wajah anak-anak yang berangkat ke sekolah satu per satu menghiasi jalan.
Saya pun berjalan menyusur danau sepanjang 26 km itu. Memasuki gerbang ‘Selamat Datang di Objek Wisata Danau Lut Tawar’, memandang kuburan di atas bukit, melewati tanpa terhipnotis penginapan termewah di Takengon ‘Hotel Renggali’, dan duduk terdiam beberapa lama di taman yang sengaja diperuntukkan buat wisatawan Lut Tawar. Taman yang tak terpelihara dan dipenuhi tahi kuda.
‘Bagaimana caranya berperahu menyusuri air danau,’ pikir saya berjalan mendekati danau. Namun semakin dekat, semakin berlumpur tanah, membuat saya mengurungkan niat. Kabut terangkat, danau biru mengemas oleh cahaya mentari yang jatuh. Saya terpesona oleh perahu yang membelah danau, kerambah-kerambah yang mengapung di tepi danau, mengikutinya turun ke bawah.
“Kakak mau apa,” seorang pemuda menghentikan langkah saya yang baru menerobos pagar suatu lahan.
Saya tunjuk kerambah jauh di bawah dan kamera. “Ah.. itu milik abang saya,” katanya mulai ramah.
“Ooo.. ikan apa saja yang dibiakkan di sana?”
“Gurameh, ikan mas..”
“Banyak hasilnya?”
“Tergantung modalnya Kak. Makin banyak kerambah tentu makin banyak untungnya.”
Saya mengangguk, mengucapkan terima kasih sambil melambaikan tangan kepada sang pemuda, abang, dan teman-temannya. Semuanya berperut ‘flat’.
Saya menuju lahan pertanian subur di sepanjang punggung pegunungan dan lembah di kejauhan. ‘Ada juga orang gayo yang bertani,’ pikir saya, mempercepat jalan menuju ke hijaunya sawah. Dalam literatur yang saya baca, orang gayo dikenal sebagai pemilik kebun kopi, bersahabat erat dengan tetangga transmigrasi jawanya yang juga menanam kopi.
Hari mulai panas. Perut melilit. Saya masuki Dusun Atun Dulang, Dusun Bur Sile, dan sebuah warung makan tepi jalan dengan kain spanduk bertuliskan
Ikan Bakar 12 Rempah. Gule Junu Awas 12. Nasi Putih Beras Kampung
“Menu apa itu? Enakkah?” tanya saya, dijawab senyum seorang pemuda yang sedang memanggang ikan. Sebuah rumah makan besar di tepi danau seolah melambaikan tangan, rumah makan yang sepi dan tutup pula. Alamak, lebih baik saya pulang naik angkot dan segera mencari hotel. Kembali saya lirk, baik si pembakar ikan maupun lelaki di sekitarnya berperut rata. Ahaha…
***
Ada beberapa penginapan sekelas losmen dan hotel di Takengon. Beberapa diantaranya dinamai dalam bahasa gayo. Hotel Mahara di Jalan Sengeda misalnya berarti membawa ada. Ini satu-satunya hotel yang ‘free wifi’ di tengah kota kecil yang nyaris tak kenal koneksi internet. Sedang Hotel Penemas tempat saya menginap berarti hidup senang. Pantas, tinggal semalam di hotel ini saya merasa senang, terlebih setelah menyantap mie kuah aceh dan kopi gayo yang disajikan oleh pelayan berperut rata seharga Rp 16.000.Ya, mie kuah dan kopi segera menjadi makanan favorit saya selama di Aceh. Selain sedap dan cocok dengan lidah Surabaya saya, harganya pun terjangkau. Senja hari saya habiskan dengan mencari kedai yang menjual suvenir khas gayo di Takengon. Aneh, di kota ini nyaris tak saya temukan toko suvenir. Tak banyak turiskah selama ini? Atau jangan-jangan memang kota ini tak begitu terkenal?
Seorang penjaja aneka pakaian di pasar memberikan saya sebuah nama toko suvenir, Keramat Mupakat namanya, di Jalan Lebe Kader tempatnya. Dari luar, toko ini nyempil, tak menarik perhatian. Namun berbincang dengan pemilik toko, tahulah saya kalau inilah satu-satunya keluarga gayo di Takengon yang menyempatkan waktu melestarikan tradisi. Anak si penjual yang membuat sulaman kerawang gayo. Kalau mau beli, jauh-jauh hari mesti pesan dulu.
“Sejak pln sering mati, susah bagi anakku menyelesaikan kain tenun sesuai jadwal,” keluh ine, panggilan ibu dalam bahasa gayo. Matinya pln membuat sebuah kain sulam kerawangyang biasanya bisa selesai 2-3 hari menjadi seminggu. Akhirnya saya pilih membeli tas perempuan kecil, dompet, dan tempat hp dengan jahitan pola gayo yang kuat. Ama, panggilan bapak dalam bahasa gayo, tersenyum menyodorkan pesanan saya. Lagi-lagi perutnya ‘flat’. Amboi…setengah baya pula !
***
Selama menginjakkan kaki di Takengon rasanya susah berinteraksi dengan penghuni asli, orang gayo. Entah mengapa, mereka berkesan ‘dingin’, seperlunya, dan agak sombong. Itu kesan pertama. Soalnya, mereka tak pernah menegur kita lebih dulu, tersenyum, apalagi basa-basi bertanya ini itu tentang kita.Pernah saya menanyakan hotel terdekat yang terjangkau kepada seorang lelaki gayo. Dia langsung menjawab pertanyaan saya, setelah itu cuek seolah saya tak pernah berada di situ. Bengong saya dibuatnya, menggerutu sambil meninggalkannya. Tapi keterangannya tepat sekali, dari titik hingga koma. Hehehe…
Suasana kaku dan seperlunya ini segera mencair ketika saya masuk ruang kopi keesokan paginya. Warung kopi itu baru buka, sayalah konsumen pertama. Tak ada lelaki kongkow di sana, tak seperti warkop yang dipenuhi para pejantan sejak pagi hingga tengah malam.
“Kopi hitam,” teriak saya.
“Oke Kakak. Kakak pasti bukan orang sini.” Saya mengangguk.
“Darimana Kak, kemarin sore saya lihat Kakak sibuk motret di depan dan di jalan…”
Ah, perhatian juga dia. Maka dimulailah perkenalan awal, cerita ini itu hingga saya kemudian diperkenalkan kepada kawan-kawan si penjual kopi, bahkan disuguh kue gratis.
“Abang orang sini juga ya?” saya lirik perutnya yang gendut.
“Bukan, saya orang Sigli, Kak,” jawabnya, membuat hati saya bertepuk tangan. ‘Apa kubilang’ sahut suara kecil di otak..
“Kalau kawan saya ini gayo asli,” tambahnya, sambil menarik seorang lelaki berperawakan tirus - tinggi dan kurus, serta agak gelap kulitnya dari motor yang berhenti di depat warkop.
Armia namanya. Memang suku gayo, tapi bukan gayo asli Takengon. Kok?
“Orang Takengon yang asli adalah gayo bermarga. Saya tak punya marga,” katanya.
“Oya, dimana mereka sekarang?”
“Kakak bisa menjumpainya di Kampung Bebesen, 3 km dari sini,” katanya.
Dari si Sigli dan Armia, si penjual cabri, cablak atau cabe inilah saya tahu kalau orang gayo di Takengon - baik yang bermarga atau tidak - telah tersingkir ke pinggir kota. Kota kini dipenuhi pendatang, orang-orang dari Medan, Padang, Jawa, juga Banda Aceh. Umumnya para pendatang ini menjadi pedagang. Sementara orang gayo lebih suka menjadi pegawai negeri seperti guru, petani kopi, padi di pinggiran seperti daerah Jagong, Batulintang, Welira.
Beberapa orang gayo bahkan tinggal terisolasi di Seurule dan Samarkilang yang tak ada akses jalan beraspal atau angkutan. “Kalau kemana-mana mereka numpang truk,” tambah Armia, penduduk asli Kampung Asir-asir. Asir-asir sendiri artinya rumput dalam bahasa gayo.
***
Saya putuskan pergi ke Bebesen pagi itu setelah sarapan. Walau dihuni suku asli gayo bermarga, Bebesen pukanlah kampung tradisional.Rumah modern memenuhi kampung itu. Ada masjid dan pondok pesantren yang menandakan Bebesen dihuni oleh muslim.Ada tiga marga yang dikenal dalam masyarakat gayo di Bebesen, yaitu monte, sibro, melala dan lingga. Keempat marga ini memiliki kemiripan dengan marga karo di Tanah Karo. Marga melala misalnya di Tanah Karo dikenal sebagai melalatoa. Setelah ditelusur ternyata setelah kerajaan Aru diserang Aceh, banyak orang karo di Tanah Karo menyebar ke berbagai tempat, misalnya ke Deli Sedang, Langkat, atau Aceh Tengah. Keturunan Karo di Takengon salah satunya.
Tepat di sebuah gapura bertuliskan kodim 106 koramil 02, saya melihat dua lelaki menuntun dua kuda. Wow, pikir saya, apa mau ada pacuaan kuda. Setahu saya pacuan kuda maupun kesenian tradisional Didong hanya dimainkan pada bulan Agustus.
Ketika akhirnya saya meninggalkan hotel, duduk di terminal Kampung Kemili menunggu angkot ke Lhokseumawe, seorang lelaki gagah mendekat. Tinggi, gelap, telinga bertindik, dan sungguh atletis. Lagi-lagi dia orang gayo bermarga melala. Bahkan kemudian sopir L300 yang membawa saya ke Lhokseumawe pun gayo bermarga Monte. Sayang perutnya agak gendut. Kerja sambil duduk mungkin membuat lemak menumpuk di dekat perut. Apalagi di setiap perhentian ia makan. Yaaa.. tak seksi lagi.
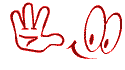






0 saran,Bagaimana Menurut Anda??klik disini:
Posting Komentar