Aku membayangkan ibukota itu pastinya rapi. Mode transportasi akan memudahkan setiap mobilitas penghuninya. Jalan-jalannya tentu rapi. Sepertinya jakarta itu bersih. Maksudku ya bersih lingkungannya, ya bersih birokrasinya, ya bersih pemeritahannya. Kan itu pusat atau semacam episentrum penyelenggaraan negara. Kalau kotor, mana bisa mengatur. Kalau ibarat sapu, maka hanya sapu yang bersih yang akan membersihkan.
Pasti orang-orang kaya yang ada di sana. Ah, aku juga mau kaya nanti.
Aku lihat di TV itu banyak gedung yang wow tinggi-tinggi. Dalam hatiku, “Apa yang dikerjakan orang di sana?” Aku mengingat ayahku. Sebagai tukang servis mesin jahit, ia tak butuh berada di gedung macam itu. Tapi itu yang membuatku penasaran. “Kerja apa ya orang-orang di dalam sana itu?” Maka, pendek kata, sepertinya aku harus ke Jakarta.
Aku tak tahu bagaimana cara ke sana. Tapi sungguh, aku ingin ke tanah Batavia itu. Setahuku, hidup di Jakarta itu mahal. Sekali makan, ya minimal tiga kali lipat harga di Blitar. Kalau di Blitar kan dua ribu sudah kenyang. Lagipula, aku sendiri hanya diberi uang sepuluh ribu untuk jajan seminggu. Ya kau pasti tahulah alasannya. “Uang dari mana agar aku bisa ke sana?” bisikku pada diri.
Akhirnya muncul kesimpulan. Tak pakai uang. Ya tak butuh uang aku ke Jakarta. Waktu itu aku kelas tiga SMA. Jadi ini kesempatanku untuk bisa melanjutkan sekolah ke Jakarta. Langsung saja melintas sebuah nama. Sebuah kampus terbaik di negeri ini. Universitas Indonesia. Aku harus ke sana, harus.
Dalam kaca mata marketing, maka yang aku alami ini namanya top of mind. Kalau soal, kampus, ya yang jadi top of mind tentu UI.
Aku cari cara bagaimana masuk kampus itu. Sebuah kampus yang jaket almamaternya berwarna kuning, yang siapapun akan bangga memakainya, lalu bekata, “I’m the yellow jacket!” keren bukan? Aku sering lihat itu di TV. Kata orang, banyak menteri lulusan kampus itu. Dalam hati, “Ya iyalah….”
Aku sampaikan pada ibuku kalau aku ingin ke jakarta, dan kuliah di UI.
Aku ingat, muka beliau menunjukkan mimik kesenangan. Mungkin kau menerka, alasannya karena aku akan mengukiri diri dengan ilmu di universitas terbaik, tapi bukan itu saja. Ini adalah kali pertama klan keluargaku untuk bisa melihat anggotanya berkuliah. Kau tahu, dengan konteks berbeda, sebuah peristiwa juga punya efek berbeda-beda. Inilah contoh kaidah itu.
seingatku aku dulu mengorek informasi di BK. Akhirnya aku temukan cara ke UI, PMDK. Namanya dulu PPTK, kalau tak salah. Sebuah jalur masuk tanpa tes tetek bengek. Hanya kirim foto kopi rapor saja dan isi biodata. Ekspektasiku begitu besar saat itu. Ingar bingar nama Jakarta juga membuat kemauanku makin kuat saja. Aku kirim dokumen aplikasiku itu.
Akan tetapi, sepertinya ekspektasi itu bertepuk sebelah tangan. Karena tak didukung partner yang berkorelasi positif, bangunan ekspektasi itu roboh sekaligus. Kampus terbaik itu menolak menerimaku. Mungkin baginya, penolakan ini biasa saja, ya sekedar meniup debu yang tak berarti, tak dikenali. Tak sesulit mendepak debu dari pundak. Tapi bagiku, depakan itu merobohkan bangunan impianku. Tentu membuat orang di sekitarku juga tak enak, apalagi ibuku.
Aku sendiri merasa agak berkhianat. Aku sendiri yang membuatnya senang, tapi aku juga yang membuatnya kesakitan, dalam hati. Mungkin bagi kau ini hal yang lumrah lah, tapi bagi keluargaku, kerobohan ini agaknya membuat kami patah arang. Pupus sudah turning point harapan kami. Sudah, sepertinya UI masih jauh panggang dari api.
Memang nasi sudah menjadi bubur. Yang dulu kekar kini layu. Tapi aku ingat, kata seorang ustadz, sebaiknya bubur itu dijadikan bubur ayam. Artinya alternatif itu masih terbuka, asal aku mau mencari alternatif itu. Robohnya impianku ternyata ditanggapi lunak oleh ibuku meski aku tahu beliau kecewa. Ia terus katakan padaku,
“Tak usah kau gerami reruntuhan itu, lebih baik buat bangunan lain. Tuhan itu selalu tahu apa mau makhluknya. Cuma Dia lebih tahu kapan waktu untuk memenuhinya, jauh lebih tahu.”
Agaknya ada kembali sinar harapan, meski masih setitik-setitik nan tercerai . Tapi kalau mau mengumpulkan yang terserak itu, pastilah terkumpul juga. Kutatih energiku. Agak terseok-seok. Tapi harapan sang ibu membuat yang terseok itu tetap konsisten.
Sampai saatnya, aku pun menerima jawaban. Ini dari Tuhan, mungkin. Ketika aku bergabung dalam sebuah forum diskusi organisasi eksternal sekolah yang selama ini aku ikuti, aku mendapati sebuah lembaran kertas berisi sebuah informasi. Onggokan kertas itu memang hanya selembar, tapi informasi yang ada di dalamnya menebarkan aroma dunia. Betapa tidak, sepertinya alternatif itu sekarang ada di depanku. Ada kesempatan beasiswa di sebuah universitas di ibukota. Saat itu aku tak begitu kenal dengan kampus itu.
Aku telusuri di website. Kampus itu masih berumur 10 tahun, ya seumuran anak kelas 3 SD. “Bisa apa anak seumur kencur itu?” Tapi, kampus itu berani menawarkan sebuah program beasiswa berskala nasional.
Tak tanggung-tanggung, seratus anak penerima akan menerima 100 juta per anak untuk 4 tahun studi. Jumlah uang itu 60 kali lebih, bila dibandingkan penghasilan perbulan ayahku yang sekitar 1,5 juta, itupun tak pasti.
Aku pakai logika sederhana saja. Meski kecil, tapi ia berani menggelar program semacam itu. Pikirku, meski tak tenar, kampus ini potensial. Dan pada saatnya potensi itu akan menyeruak nan mekar ke permukaan dan menyadarkan dunia bahwa
“We are small, but giant.”
Aku penuhi semua persyaratan dokumennya. Seminggu lebih aku siapkan. Sejenak ini membuatku lupa pada bangunan lamaku. Pondasi bangunan impian ke UI sejanak aku kesampingkan. Aku kirimlah dokumen itu. Aku ini masih ingin ke Jakarta.
Pendek cerita, aku lolos ke tahap wawancara. Yang paling mendebarkan adalah ketika aku ditanya,
“Ceritakan tentang dirimu?”
aku sadar, ini pertanyaan mudah, tapi jawaban akan menjadi sulit kalau aku bersandiwara. Kau tahu kenapa? Pertanyaan itu akan berlanjut sesuai jawaban. Semakin aku bersandiwara, maka semakin kelihatan aku ini orang bermuka dua, dan semakin jelas bahwa aku pasti, pasti tak diterima.
Tapi untungnya tidak. Itu hanya informasi buatmu. Semoga kau tak melakukannya ketika ada di posisi sepertiku.
Aku ingat sekali. Malam itu tanggal 16 Agustus, dua tahun lalu. Aku ke warnet untuk melihat pengumuman. Sebenarnya, seharusnya dua hari sebelumnya sudah diumumkan. Tapi sudahlah. Yang jelas tanggal 16 itu menjadi malam paling menentukan. Ini adalah bangunan impianku yang kedua. Kalau roboh lagi, ya sudah. Aku tak akan menyentuhkan kaki pada episentrum negeri. Aku akan meringkuk saja di bumi bung karno.
Tapi ternyata Tuhan merestui berdirinya bangunan kedua. Aku diterima. Program itu bernama Paramadina fellowship 2008. Akhirnya ada juga anggota klan keluargaku yang berkuliah. Tentu buatmu tak terlalu membanggakan, tapi bagiku ini ini luar biasa membanggakan. Kau tahu kenapa? Karena malam itu ketika aku sampaikan bahwa aku terpilih, ibuku tak henti-hentinya mengucap puji pada Tuhan,
“Alhamdulillah….alhamdulillah…alhamdulillah..”
Dan paginya aku lihat ia bersujud lama sekali, mungkin sujud syukur.
Jadilah anak tukang servis mesin jahit ini berangkat ke ibukota. Aku ingin segera mengonfirmasi khayalanku tentang kota batavia ini. Tapi kenyataannya ketika aku lihat, ternyata ironi. Ya, ironi. Kau tahu maksudnya kan? Kau baca ulang paragraf kedua awal ceritaku ini, lalu pikirkan saja kebalikannya. Ya itu gambarannya ibukota.
Kawan, tebak dimana aku sekarang? Aku sekarang ini sedang berada di bangunan lama, tapi bukan sebagai penghuninya. Aku orang lain di sini, di UI. Memang aku akui, aku telah menjadi penghuni bangunan impian alternatifku, aku telah menjadi bagian Universitas Paramadina.
Tapi jujur, fondasi impianku yang pertama itu masih membekas di dadaku. Melihat UI membuatku sesak, meski sedikit. Karena ia pernah jadi impianku. Ah, mungkin masih ada keinginanku untuk menjadi bagiannya, meski sedikit.
UI, Depok, 7 Maret 2010
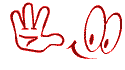






0 saran,Bagaimana Menurut Anda??klik disini:
Posting Komentar